Cerpen : Getar Lidah di Bukit Barisan
Oleh: Vera Ade Alexsa
Di lekuk Bukit Barisan yang memeluk desa Lingga Julu, Karo, Sumatera Utara,
bersemayam seorang pemuda bernama Tama. Bukan ketampanan rupa yang membuatnya dikenal, melainkan Getar Lidah, setiap kata yang lolos dari bibirnya menjelma kenyataan, bak petir menyambar di siang bolong. Tama tak berdosa, namun lidahnya adalah pedang bermata dua, menebar berkat dan laknat tanpa bisa ia kendalikan.
Matahari pagi menyinari ladang-ladang jagung yang menguning. Burung-burung berkicau riang, menyambut hari baru. Namun di Lingga Julu, senyum penduduk memudar. Musim paceklik mencengkeram desa. Ladang jagung merana, tulang-tulang daunnya mengering, menengadah ke langit yang enggan menumpahkan air mata.
Tama, kalut menyaksikan jerih payah keluarganya terancam. Ia telah bekerja keras membajak sawah, menanam bibit, dan merawat tanamannya. Namun, kekeringan telah merenggut semua harapan.
Tanpa sadar, Tama menggerutu, “Mampuslah ladang ini! Takkan ada setitik pun rezeki yang tumbuh di tanah terkutuk ini!”
Seketika, tanah mereka berhawa panas membakar sisa-sisa kehidupan. Ladang Tama berubah menjadi hamparan abu yang bisu. Angin berdesir pilu, membawa serta debu dan penyesalan.
Rasa bersalah menghantam Tama. Ia sadar, getar lidahnya adalah kutukan bagi diri sendiri dan sesama. Ia telah menghancurkan harapan keluarganya dengan kata katanya sendiri. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan Lingga Julu, mencari penawar di kaki Bukit Barisan.
Perjalanan Tama membawanya ke pertapaan sunyi. Di sana, ia bertemu Guru Sibayak, sosok renta dengan mata setajam elang. Keriput di wajahnya adalah peta pengalaman hidup.
“Nak, getar lidahmu adalah cermin amarah yang berkarat di hatimu. Ia lahir dari dendam yang kau pelihara. Untuk menjinakkannya, kau harus belajar memaafkan, meredam ego, dan menyatu dengan alam,” sabda Guru Sibayak.
Berhari-hari ia bermeditasi di tepi air terjun Sipiso-piso, membiarkan gemuruhnya membungkam amarah. Ia belajar menari landek, merasakan denyut kehidupan dalam gerak 2 gemulai. Ia mendaki Gunung Sibayak, menghirup napas hutan pinus, membiarkan kedamaian merasuk ke dalam jiwa.
Dalam kesunyian, Tama merenungkan kesalahan-kesalahannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia dikuasai oleh amarah dan kebencian. Ia tidak pernah belajar untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya. Ia juga tidak pernah menghargai alam yang telah memberikan kehidupan kepadanya. Ia teringat akan ucapan-ucapan pedas yang pernah ia lontarkan kepada tetangga yang iri terhadap hasil panennya di masa lalu, kata-kata yang kini ia yakin telah menjadi bibit petaka kekeringan. Penyesalan yang mendalam mengoyak jiwanya, namun di saat yang sama, ia merasakan beban dendam yang selama ini menghimpitnya mulai terlepas.
Setahun berlalu. Tama kembali ke Lingga Julu. Desa itu tak lagi muram. Gotong royong mengalir deras, bahu-membahu membangun irigasi, menanam bibit baru. Senyuman di wajah penduduk.
Tama tersenyum, “Desaku telah menemukan kekuatannya sendiri”. Ia melihat ladang-ladang yang mulai menghijau, bukan karena mukjizat mendadak, melainkan karena keringat dan kebersamaan
Namun, badai kembali menerjang. Datanglah Tuan Silalahi, saudagar dari Medan, dengan janji manis membeli seluruh tanah Lingga Julu.
“Kalian akan kaya raya! Biar kutambang belerang dari perut gunung ini”, ujarnya dengan mata berbinar serakah. Ia didampingi oleh beberapa pengawal bertubuh besar yang membuat warga segan.
Warga desa tergiur. Impian memiliki mobil, rumah gedong, dan perhiasan emas membutakan mata hati mereka. Mereka lupa akan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Mereka mulai berandai-andai tentang kehidupan mewah di kota, melupakan tanah leluhur yang telah menghidupi mereka turun-temurun. Tua-tua desa yang semula teguh menjaga adat pun mulai goyah. Hanya Tama yang melihat bahaya di balik senyum Tuan Silalahi. Ia mencoba memperingatkan, namun suaranya tenggelam dalam gemerlap rupiah.
“Tanah ini warisan! Bukan sekadar komoditas!” teriak Tama, namun hanya disambut tatapan sinis.
Di persimpangan batin, Tama merenung di bawah rindang pohon beringin, pohon keramat tempat para leluhur biasa bermusyawarah. Ia merasakan bisikan angin, seolah suara para pendahulunya memohon perlindungan. Jika ia menggunakan Getar Lidah untuk mengutuk Tuan Silalahi, ia akan menjadi monster yang ditakuti, mengulang kesalahan masa lalu yang didasari amarah. Namun, jika ia diam, Lingga Julu akan lenyap ditelan keserakahan, alam akan rusak, dan identitas mereka akan hilang. Dengan berat hati, ia memilih menyelamatkan desanya, namun kali ini, ia akan menggunakan kekuatannya dengan dilandasi kasih dan niat baik, seperti yang diajarkan Guru Sibayak.
Tama menghadang Tuan Silalahi di gerbang desa, tepat di bawah spanduk reyot
bertuliskan “Selamat Datang di Lingga Julu.”
“Tuan, tanah ini adalah ibu kami. Ia menghidupi kami, memberi kami identitas. Kau takkan pernah bisa membelinya!” ucapnya dengan suara bergetar, namun penuh ketenangan, tanpa sedikit pun amarah. Ia fokus pada inti permasalahannya: tanah adalah sumber kehidupan, bukan tambang kekayaan sesaat.
Tuan Silalahi tertawa mengejek, “Omong kosong! Anak muda, minggir atau kau akan menyesal!”
Tama mengabaikan ancaman itu. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat ajaran Guru Sibayak tentang memaafkan. Ia membuka matanya dan menatap Tuan Silalahi dengan tatapan penuh iba, bukan kebencian.
“Aku memaafkan keserakahanmu, Tuan Silalahi,” ucap Tama lembut, suaranya terdengar seperti bisikan, namun semua orang mendengarnya. “Dan aku mendoakanmu agar kau menemukan harta yang sesungguhnya di tempat yang lain, bukan dengan menghancurkan hidup kami.”
Seketika, Tuan Silalahi limbung. Kulitnya memerah, tubuhnya menggeliat kesakitan. Ia merasakan sensasi terbakar, bukan karena api, melainkan karena rasa malu dan penyesalan yang tiba-tiba menyeruak di hatinya. Keinginan serakah yang tadinya menguasai dirinya mendadak lenyap, digantikan rasa sesak karena telah menipu banyak orang. Ia meraung, “Apa yang kau lakukan padaku, anak muda?!”
Warga desa terkejut. Mereka menyaksikan sendiri kekuatan Getar Lidah Tama yang kini terasa berbeda, tidak mematikan, tetapi melumpuhkan niat jahat. Ketakutan dan penyesalan mencabik hati mereka. Mereka tersadar, kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan kebersamaan dan kearifan lokal. Tatapan mata mereka beralih dari koper berisi uang Tuan Silalahi, menuju ladang yang mulai menghijau.
Tuan Silalahi, yang telah kehilangan kesombongannya, memegang dadanya dan berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia meninggalkan Lingga Julu, dan janjijanji manisnya ikut menguap bersama debu jalanan.Dengan berurai air mata, warga desa memohon ampun kepada Tama. Mereka berjanji akan menjaga Lingga Julu, melestarikan adat istiadat, dan menghormati alam.
Tama memaafkan mereka. Ia merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Getar lidahnya tak lagi mematikan, melainkan menjadi pelindung desa, sebuah kekuatan yang hanya muncul saat didorong oleh cinta dan kearifan.
Matahari terbenam di ufuk barat, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa serta aroma bunga dan harapan. Di Lingga Julu, kehidupan terus bersemi, dijaga oleh kearifan dari sebuah “Getar Lidah” yang telah menemukan kedamaian Sejak saat itu, Tama menjadi penasihat desa. Ia mengajarkan warga untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Ia selalu mengingatkan bahwa setiap kata adalah benih, dan hanya benih kebaikan yang akan menumbuhkan masa depan yang indah. Lingga Julu menjadi desa percontohan, makmur sejahtera tanpa kehilangan jati diri. Laki-laki dan perempuan kembali menarikan landek di tengah ladang yang subur, merayakan panen yang melimpah. Mereka tidak hanya merawat tanah, tetapi juga kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Dan Tama, “Si Getar Lidah”, dikenang sebagai pahlawan yang menyelamatkan desanya dengan kekuatan cinta dan kearifan. Ia telah menaklukkan bukan hanya musuh, melainkan amarah di dalam dirinya sendiri.
BIODATA PENULIS :
Nama Penulis : Vera Ade Alexsa
NIM : 2420100035
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Musyrifah Asrama : D-1


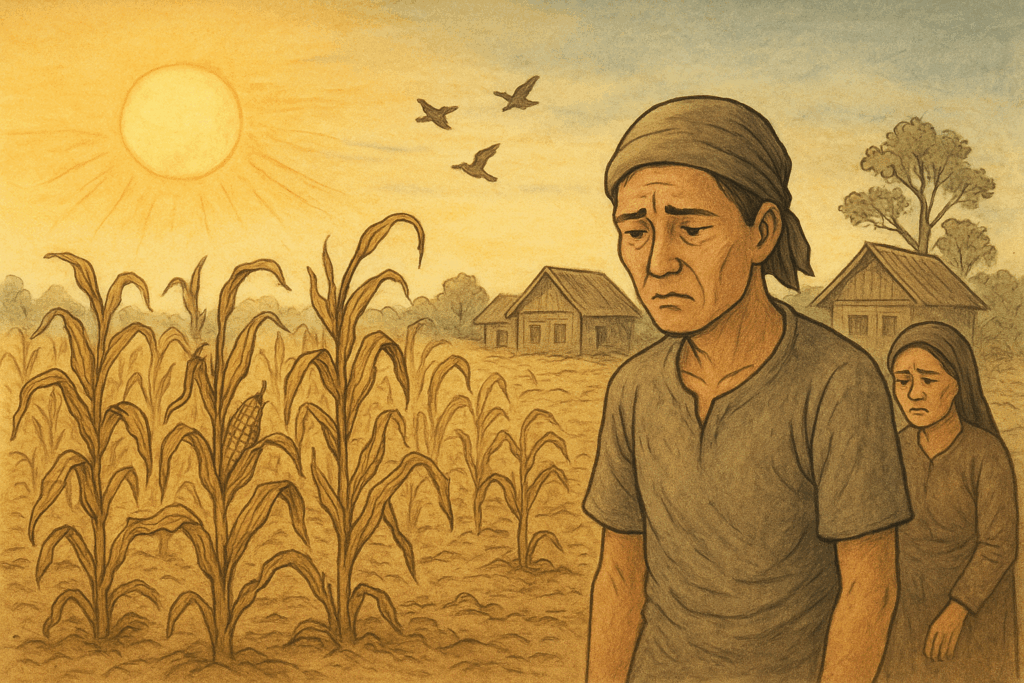
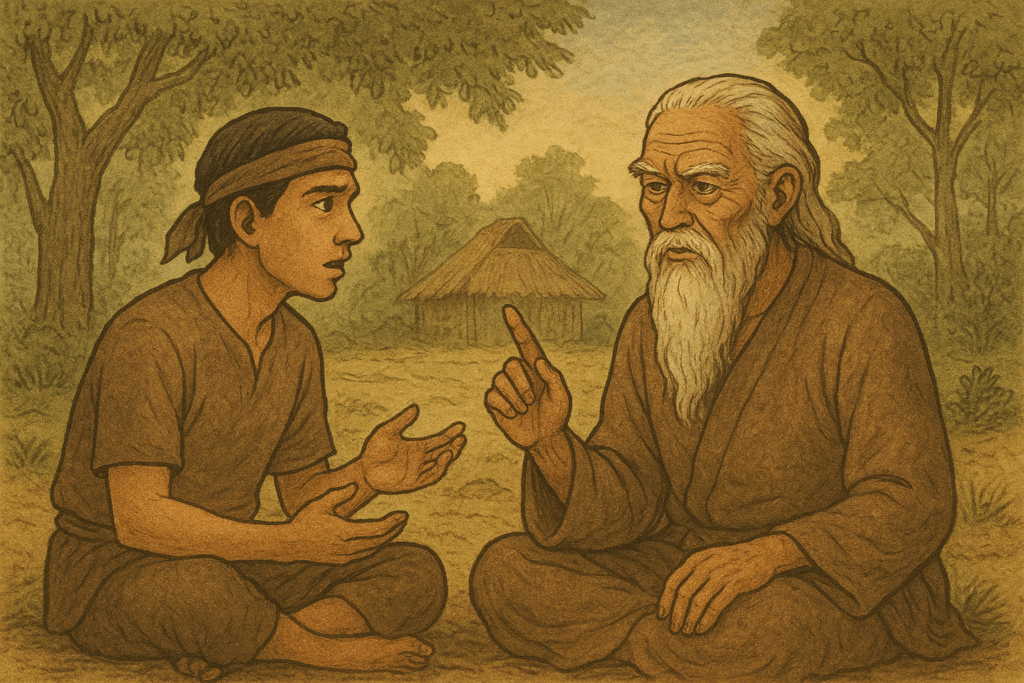






3 Comments